Saya melihat dunia pendidikan kita berada di tengah arus perubahan yang deras. Dorongan untuk meningkatkan kompetensi digital di kalangan pendidik terasa begitu kuat, seiring dengan masuknya teknologi seperti Kecerdasan Artifisial (AI) ke dalam wacana pembelajaran sehari-hari.
Ini adalah sebuah tuntutan zaman yang tak terhindarkan. Namun, di tengah gegap gempita ini, saya merasakan sebuah kekhawatiran yang mendalam. Saya khawatir kita terjebak pada euforia penguasaan alat, di mana kehebatan seorang pendidik diukur dari seberapa banyak teknologi baru yang bisa ia operasikan.
Bagi saya, jika kita hanya berfokus pada apa teknologinya tanpa bertanya mengapa dan bagaimana ia digunakan secara humanis, kita berisiko kehilangan jiwa pendidikan itu sendiri. Ini adalah antitesis dari semangat kurikulum baru yang saya yakini bertujuan untuk transformasi cara berpikir, bukan sekadar akumulasi alat digital.
Hambatan Sesungguhnya: Krisis Visi, Bukan Krisis Akses
Banyak yang berdalih bahwa hambatan utama teknologi adalah keterbatasan akses atau kurangnya pelatihan. Namun, sebagai seorang yang berkecimpung di dunia teknologi pendidikan, saya melihat ada hambatan yang lebih fundamental, yakni hilangnya visi humanis.
Ini adalah krisis jiwa yang ironisnya coba dijawab oleh arah kebijakan pendidikan kita. Saya melihat semangat kurikulum baru kini secara eksplisit mendorong terciptanya suasana belajar yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful) melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik.
Senada dengan itu, saya menafsirkan muatan kurikulum tentang Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) pun tidak dirancang untuk mencetak operator gawai, melainkan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta pemecahan masalah dengan landasan etika dan human-centered mindset.
Ketika guru-guru sibuk menguasai puluhan aplikasi tanpa memahami filosofi di baliknya, menurut saya mereka justru melakukan dehumanisasi: mereduksi anak didik menjadi objek yang harus "diproses" dengan digital tools. Inilah yang saya pahami sebagai kegagalan dalam proses hominisasi dan humanisasi yang diajarkan Romo Driyarkara. Saya yakin, masalahnya bukan pada keterbatasan WiFi, tetapi ketika kita menggunakan teknologi tanpa jiwa.
Romo Mangun, Freire, dan Gema Mereka dalam Kurikulum Baru
Jauh sebelum arah kebijakan ini dirumuskan, saya selalu teringat pada para pemikir besar yang telah meletakkan fondasinya. Romo Y.B. Mangunwijaya mengajarkan bahwa "pendidikan sejati adalah pendidikan yang memerdekakan". Dalam konteks teknologi, saya memaknainya sebagai upaya teknologi untuk membebaskan anak dari belenggu menjadi konsumen pasif.
Saya sering melihat sebuah pendekatan di mana seorang guru memutar video YouTube tentang "Pentingnya Menjaga Kebersihan" lalu meminta siswa merangkumnya. Bagi saya, ini adalah bentuk pemenjaraan anak dalam pola konsumsi informasi yang pasif.
Namun, saya membayangkan sebuah pendekatan yang jauh lebih memerdekakan: seorang guru memutar video timelapse bunga mekar tanpa narasi, lalu mengajak anak-anak merefleksikan proses pertumbuhan dan kesabaran. Di sini, saya melihat teknologi tidak lagi menjadi penyampai pesan yang kaku, melainkan sebuah katalisator untuk refleksi mendalam yang menghubungkan anak dengan esensi kemanusiaannya.

 2 weeks ago
9
2 weeks ago
9










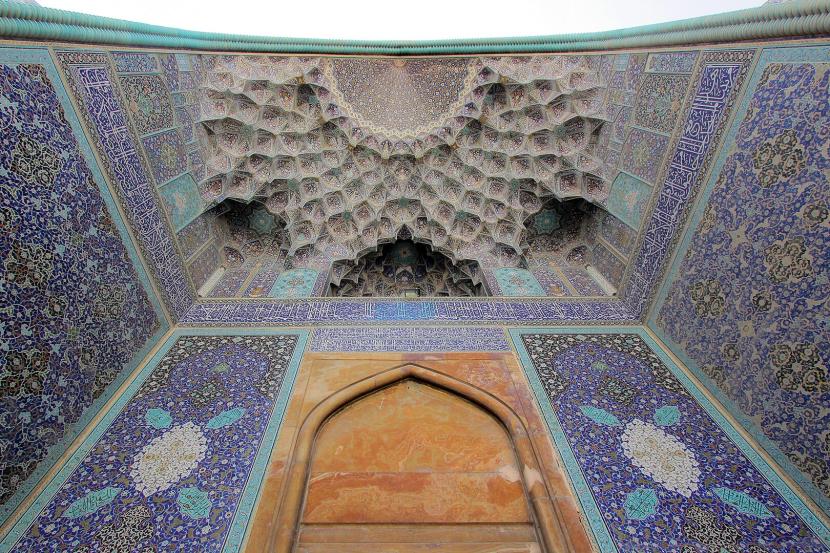



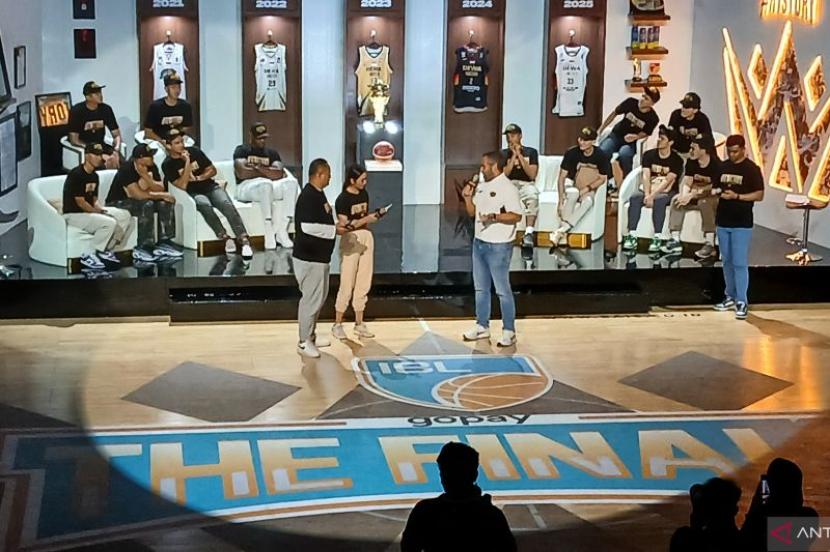




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5332436/original/003536800_1756480749-Foto_1__10_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5331162/original/030751900_1756386365-image001.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4667381/original/034639800_1701238155-Planet_Uranus.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5325256/original/067414700_1755944044-Universal_Language_0.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310493/original/086946400_1754722774-Dan_Houser__Pendiri_Absurd_Ventures_dan_Mantan_Pendiri_RockStar-fotor-20250809125727.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5246336/original/073893500_1749449043-Ally-Lifestyle-95ba78138af423e277de.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5184358/original/069718000_1744278295-Vivo_V50_Lite_01.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5197657/original/059843400_1745480602-photo_2025-04-24_14-35-41.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5316351/original/043054100_1755233091-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5314460/original/013895100_1755080788-FFWS_SEA_2025_Fall_01.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5314217/original/014846500_1755069978-WhatsApp_Image_2025-08-13_at_14.11.46.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5309898/original/050077200_1754643331-dress_brokat_outer_lengan_balon_8.jpg)

 English (US) ·
English (US) ·